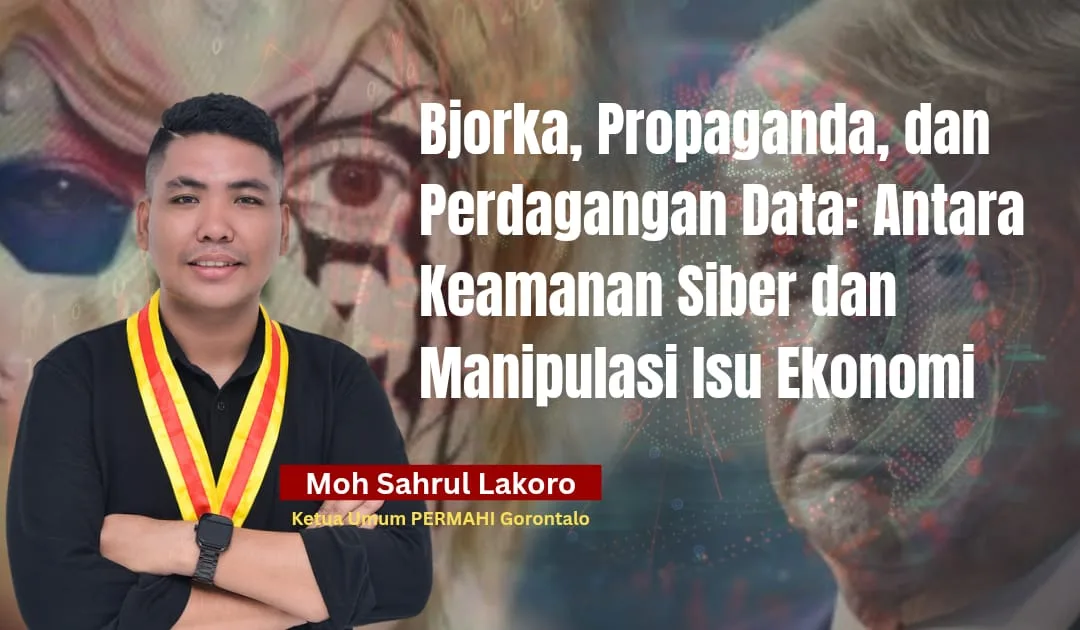Oleh: Moh Sahrul Lakoro (Ketua Umum DPC PERMAHI Gorontalo)
Nama Bjorka kembali menghantui ruang digital Indonesia. Sosok misterius yang kerap mengklaim kebocoran data pemerintah ini menjadi fenomena tersendiri. Setiap kali muncul, publik panik, media ramai, dan pemerintah sibuk menenangkan situasi dengan janji memperkuat sistem keamanan siber nasional.
Namun di balik kepanikan itu, muncul pertanyaan mendasar yang jarang disorot: apakah isu Bjorka benar-benar murni ancaman siber, atau justru bagian dari permainan politik dan ekonomi yang lebih besar?
Isu Keamanan yang Disulap Jadi Legitimasi Politik
Dalam teori securitization, isu keamanan sering dijadikan alat untuk membentuk legitimasi kebijakan tertentu. Pemerintah dapat “menyulap” ancaman menjadi alasan untuk mengesahkan kebijakan yang sebenarnya bersifat politis atau ekonomis. Pola ini tampak dalam setiap kemunculan Bjorka: negara mengklaim dirinya dalam kondisi darurat siber, lalu memunculkan narasi perlunya kerja sama internasional khususnya dengan Amerika Serikat di bidang keamanan digital dan perdagangan data.
Kebetulan, pada 2025 ini, pembahasan mengenai Kerangka Kerja Perdagangan Digital Indonesia–AS (Digital Economic Framework) sedang berlangsung. Kesepakatan tersebut mencakup klausul penting tentang cross-border data flow, yakni aliran data lintas batas negara.
Jika disusun secara kronologis, isu kebocoran data nasional yang berulang justru muncul berdekatan dengan agenda perundingan itu. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa narasi “Indonesia dalam darurat siber” dapat berfungsi sebagai alat propaganda untuk melunakkan resistensi publik terhadap perjanjian yang sebenarnya berpotensi melemahkan kedaulatan digital nasional.
Data Sebagai Komoditas Geopolitik
Dalam era ekonomi digital, data adalah minyak baru. Ia menjadi komoditas paling strategis di abad ke-21. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sedang berebut pengaruh dalam menentukan siapa yang menguasai arus data global. Indonesia, dengan 270 juta penduduk dan tingkat penetrasi internet yang tinggi, menjadi pasar data yang sangat potensial.
Bagi korporasi teknologi AS, seperti Google, Amazon, Meta, dan Microsoft, kebijakan cross-border data flow sangat menguntungkan. Dengan kebijakan itu, perusahaan asing bisa menyimpan, memproses, dan memanfaatkan data warga Indonesia di luar negeri tanpa kewajiban menyimpannya secara lokal.
Masalahnya, ketika data warga tersimpan di luar negeri, maka yurisdiksi hukum Indonesia melemah. Jika terjadi pelanggaran privasi atau kebocoran, mekanisme penyelesaiannya akan bergantung pada hukum negara tempat data itu disimpan yang tentu lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar.
Isu Bjorka: Antara Hacker dan Hegemoni
Dalam konteks ini, kemunculan Bjorka bisa dibaca sebagai pengalih perhatian strategis. Fokus publik diarahkan pada sosok misterius dan sensasi kebocoran data, sementara kebijakan strategis seperti perjanjian dagang lintas data berlangsung tanpa pengawasan kritis.
Kita seolah menyaksikan drama nasional: pemerintah tampil sebagai korban dan pahlawan sekaligus, sedangkan rakyat diarahkan untuk percaya bahwa solusinya adalah memperkuat kerja sama digital dengan negara lain. Padahal, kerja sama itu justru bisa membuka pintu bagi eksploitasi data rakyat oleh kekuatan asing.
Bentuk propaganda semacam ini bukan hal baru. Dalam kajian media, fenomena ini disebut manufacturing consent istilah yang dipopulerkan Noam Chomsky. Pemerintah dan media secara tidak langsung membentuk persetujuan publik melalui narasi ancaman dan ketakutan. Dalam kasus Bjorka, rasa takut terhadap hacker digunakan untuk menciptakan legitimasi kebijakan ekonomi yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Ketika Keamanan Mengorbankan Kedaulatan
Pemerintah tentu berhak memperkuat keamanan siber. Tetapi keamanan tidak boleh menjadi dalih untuk melemahkan kedaulatan. Ironisnya, kebijakan yang lahir dari isu kebocoran data justru berpotensi memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap sistem dan standar keamanan global yang dikendalikan negara-negara maju.
Sejak 2022, pemerintah sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun hingga kini, penegakan hukumnya lemah, dan mekanisme audit forensik atas setiap kebocoran data nyaris tak pernah dipublikasikan. Kasus Bjorka hanya berakhir pada penangkapan beberapa individu, tanpa kejelasan siapa aktor utama di baliknya.
Jika pemerintah serius menjaga keamanan data, seharusnya audit independen dilakukan secara terbuka, bukan hanya melalui pernyataan pers atau konferensi singkat. Tanpa transparansi, isu keamanan akan terus menjadi alat politik, bukan instrumen perlindungan publik.
Kedaulatan Digital: Pilar Baru Kemerdekaan
Isu Bjorka membawa kita pada refleksi yang lebih mendasar: bahwa kedaulatan di abad digital tidak lagi hanya soal wilayah darat, laut, dan udara tetapi juga tentang ruang data. Data rakyat adalah representasi identitas, perilaku, dan kehidupan sosial yang tak ternilai. Ketika data itu diperdagangkan, maka sesungguhnya yang diperjualbelikan adalah privasi dan kendali atas warga negara itu sendiri.
Sayangnya, diskursus ini jarang muncul dalam ruang publik. Wacana digital di Indonesia masih didominasi oleh isu teknis dan keamanan, bukan isu kedaulatan dan etika. Pemerintah seolah ingin menunjukkan kemampuan mengatasi hacker, tetapi belum menunjukkan keseriusan menjaga hak digital warga negara.
Dalam konteks global, banyak negara mulai menolak konsep cross-border data flow tanpa kontrol, karena dianggap mengancam kemandirian digital. India dan Brasil, misalnya, memperkuat kebijakan data localization agar data warga tetap disimpan di dalam negeri. Indonesia perlu meniru langkah serupa, bukan justru tergoda oleh janji investasi yang dibungkus kerja sama digital.
Membangun Kesadaran Publik
Kedaulatan digital tidak akan lahir dari pemerintah saja, melainkan dari kesadaran publik. Masyarakat harus memahami bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Ketika data digunakan tanpa izin, itu bukan sekadar pelanggaran privasi melainkan bentuk kolonialisme baru dalam wujud digital.
Media juga punya peran penting untuk tidak terjebak dalam sensasi hacker semata. Liputan harus diarahkan pada substansi: siapa diuntungkan dari kebijakan digital nasional, dan bagaimana pengawasan publik terhadap perjanjian internasional dijalankan. Tanpa kontrol media dan akademisi, isu Bjorka akan terus menjadi alat pembenaran bagi agenda ekonomi yang tersembunyi.
Dari Ketakutan Menuju Kesadaran
Kasus Bjorka adalah cermin. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya sistem digital negara, sekaligus betapa mudahnya ketakutan publik dimanfaatkan. Jika benar isu ini digunakan sebagai momentum untuk meloloskan kesepakatan dagang dengan AS, maka itu bukan sekadar kebijakan yang keliru, melainkan pengkhianatan terhadap kedaulatan data rakyat sendiri.
Negara boleh melawan peretas, tetapi rakyat berhak melawan manipulasi. Isu keamanan tidak boleh dijadikan propaganda ekonomi. Sebab di era digital ini, data adalah bentuk baru dari kemerdekaan, dan kemerdekaan sekali lagi tidak untuk dijual.
Tulisan ini mendorong transparansi pemerintah dalam isu kebocoran data dan menolak eksploitasi isu keamanan siber sebagai alat legitimasi ekonomi lintas negara. (*)